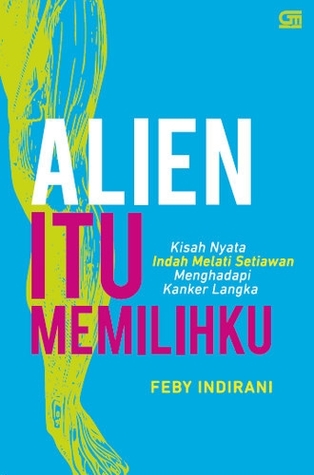Jujur saja, pada awalnya saya tidak tertarik untuk membaca buku ini. Utamanya karena desain sampul buku tersebut yang terkesan seperti buku pelajaran di bangku kuliah. Siapa sangka buku ini ditulis oleh seorang profesor psikologi bernama Angela Duckworth, dan mengangkat tema kesukaan saya, yaitu tentang cara “pintar” untuk meraih kesuksesan.
Saya mulai tertarik membaca Grit ketika melihat CEO MatahariMall, Hadi Wenas, mereferensikan buku ini di media sosial miliknya. Karena itu saya pun membeli buku tersebut, tentunya setelah sang penerbit mengeluarkan desain sampul yang berbeda.
Buku ini sempat terabaikan di rak buku karena saya sedang asyik dengan 1Q84 karya Haruki Murakami. Saya baru mendapat kesempatan membaca Grit dalam perjalanan ke Semarang dan Jogja beberapa hari yang lalu. Dan keputusan tersebut ternyata tidak salah. Saya pun kembali dengan sebuah pemikiran baru yang menyenangkan.
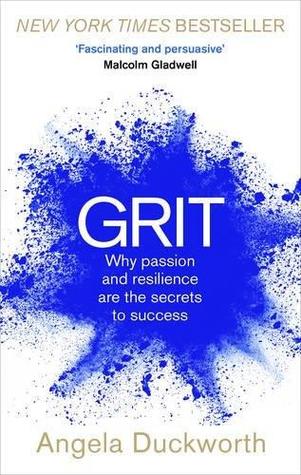
Grit
Angela Duckworth
Vermilion, Penguin Random House
Terbitan pertama 4 Mei 2016
352 halaman
Apa itu Grit?
Grit sendiri adalah istilah yang digunakan Duckworth untuk semangat dan ketekunan yang dimiliki oleh seseorang ketika tengah melakukan sesuatu. Menurut hipotesa Duckworth, orang yang bersemangat dan tekun cenderung lebih sukses dibanding orang lain yang mempunyai potensi alami (jenius) namun tidak mengiringinya dengan ketekunan.
Untuk membuktikan hipotesa tersebut, Duckworth pun melakukan penelitian terhadap para tentara yang mampu bertahan dalam kamp pelatihan West Point, peserta kompetisi mengeja National Spelling Bee, para kartunis The New Yorker, hingga tim american football Seattle Seahawks. Ia bahkan membuat sebuah alat uji khusus yang disebut Grit Scale.
Hasilnya, orang-orang dengan Grit Scale yang tinggi cenderung lebih sukses dibanding rekan mereka, terlepas dari tingkat kesejahteraan keluarga mereka, hingga berapa IQ yang mereka miliki. Berikut ini adalah beberapa contoh pertanyaan yang harus kamu jawab dalam pengujian Grit Scale:
- Apakah ide dan proyek baru bisa mengalihkan perhatian kamu dari apa yang kamu kerjakan saat ini?
- Apakah kamu kesulitan menjaga fokus ketika mengerjakan proyek yang butuh waktu beberapa bulan untuk selesai?
- Apakah kamu sering terobsesi dengan suatu hal, namun tak lama kemudian justru kehilangan minat terhadapnya?
Menurut Duckworth, ketekunan untuk berlatih keras dalam bidang apapun, merupakan wujud nyata dari Grit. Seorang atlet dengan ketekunan tinggi tentu akan menghabiskan waktu yang lebih lama untuk berlatih. Seorang kartunis yang mempunyai semangat tentu tidak akan menyerah meski telah banyak karya mereka yang ditolak penerbit.
Hal ini pun membuat saya berpikir, apakah saya merupakan seseorang dengan Grit yang rendah? Jujur, saya termasuk orang yang kesulitan untuk menjaga fokus ketika melakukan sesuatu. Ketika itu terjadi, saya cenderung untuk beralih ke pekerjaan yang lain.
Setelah membaca buku ini, sepertinya saya harus menghentikan kebiasaan tersebut. Untungya menurut Duckworth, Grit sendiri bisa ditumbuhkan. Caranya adalah dengan menetapkan target yang tinggi, kemudian bekerja keras untuk mencapai target tersebut, tidak hanya dalam waktu sehari atau sebulan, namun selama bertahun-tahun.
Baiklah, akan saya lakukan!
“Gunakan kegagalan dan masalah sebagai kesempatan untuk menjadi lebih baik, bukan alasan untuk menyerah.”
Kisah Ta Nehisi Coates

Untungnya, di akhir buku, Duckworth pun menceritakan kisah tentang seorang penulis bernama Ta Nehisi Coates. Karena saya sendiri kini berprofesi sebagai jurnalis dan penulis, maka saya pun merasa bisa mengambil inspirasi dari cerita tersebut.
Delapan tahun yang lalu, Coates dipecat oleh majalah Time. Meski sang istri tetap mendukungnya, namun Coates tetap merasa bingung karena mereka pun telah mempunyai anak yang harus diberi nafkah.
“Saya membenturkan kepala ke dinding, namun tidak ada juga ide tulisan yang keluar. Saya bahkan sempat berpikir untuk banting setir menjadi seorang pengemudi taksi.”
Namun Coates akhirnya berhasil bangkit. Ia mencurahkan rasa frustasinya ke dalam sebuah buku, yang akhirnya justru menjadi kisah yang kuat. Menurut Coates, setiap proses menulis sebenarnya merupakan petualangan dari sebuah kegagalan ke kegagalan lain.
“Di awal, sebuah tulisan pasti akan berantakan, yang kemudian memenuhi pikiran kamu saat tidur. Ketika bangun, kamu harus membenahi tulisan tersebut. Jika beruntung, tulisan tersebut akan membaik, namun jika tidak maka kamu harus terus membenahinya. Lakukan itu terus menerus, hingga akhirnya tulisan kamu pun layak dibaca orang lain,” jelas Coates.
Sebagai tambahan setelah membaca Grit, ada baiknya kamu juga membaca buku lain dengan tema yang seperti melengkapi buku ini. Saya sarankan untuk membaca The Power of Habit karya Charles Duhigg dan Outliers karya Malcolm Gladwell. Selain itu, coba saksikan juga rekaman ulasan tentang Grit yang disampaikan oleh Angela Duckworth di TED Talk yang tersedia di YouTube.